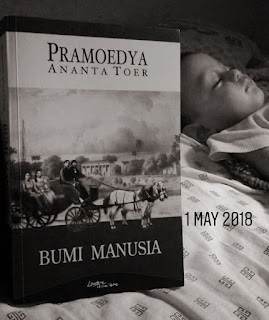Bumi Manusia, a book review
Bumi Manusia hampir jadi buku nomer tiga di daftar buku yang gagal (tepatnya: sulit) gue selesaikan setelah Cala Ibi dan Max Havelaar. Ga ngerti, deh, Bumi Manusia ini kok jauh dari ekspektasi gue kalo dibandingkan dengan Gadis Pantai—my Pram’s all time favorite. Berkali-kali putus-nyambung, overlap sama beberapa buku laen, mencoba baca lagi dan rasanya susah banget menghidupkan soul-nya sampe bisa khatam smoothly.
Ya mungkin salah gue juga, sih, over
expectation. Tapi, coba, ya. Bumi Manusia ini buku paling populer di
rangkaian tetralogi Pulau Buru, loh. Mungkin karena buku pertama sih, ya. Di Bumi
Manusia karakter Nyai Ontosoroh dan Minke sangat kuat sementara Annelies yang why-she-should-be-like-that
banget. How can Nyai has a daughter like Annelies, why?
Emang kenapa?
Menurut gue dia over manja,
cheesy, and sorry to say: beyond alay. Kalo kata laki gue sih itu karena
nyokapnya yang keras ke dia. Ini bukan spesifik soal karakternya dia, tapi
lebih ke sikapnya setelah kenal Minke. And oh, she looked like didn’t learn
from her parents relationship. Bumi Manusia ini kan komposisinya lebih
banyak cerita cintanya daripada isu sosial-politiknya, jadi ya, mau ga mau gue akhirnya
banyak skip paragraf-paragraf di mana Annelies jadi perempuan lemah
gitu. *rolled eyes*
Segitu kharismatiknya ya, si
Minke ini sampe bikin satu perempuan bidadari-like jadi pesakitan. X)) Ya gimana, sakitnya
aneh banget menurut gue. Semacam perpaduan demam cinta, malarindu, dan kejiwaan
yang terguncyang. Hahah. Sampe-sampe butuh pemeriksaan intens oleh seorang
dokter keluarga yang mana dokter itu hands over his job to Minke (which
was “only” a HS student, ftw).
Luaaarrrr biyasaaah.
Oke, that’s the one part, now
let’s talk the other ones.
Gue tau soal tetralogi Pulau Buru
sejak awal kuliah dulu. Sebagai mahasiswa kere yang pengen upgrade
wawasan dan gagal jadi anak jurusan sastra, gue maraton pinjem buku sastra di
perpus fakultas. Alhamdulillah, rejeki anak sholelah yang kuliah di fakultasnya
anak sastra, koleksi novel-novelnya cukup komplit. Tapi sayang, tiap mau pinjem
Bumi Manusia pasti keluar mulu.
Jadinya, gue skip ke koleksi buku Pram yang lain atau karya penulis lain
macem Dee, Ayu Utami, Eka Kurniawan, Djenar Maesa Ayu, N.H Dini, dan
sebagainya, atau buku kumpulan cerpen Kompas.
Oh, that good old days. ^^
Pergulatan Minke sebagai pemuda
pelajar pribumi (oh I hate this word) menemukan tambahan masalah ketika
ia mulai kenal Annelies. Yastralaya, gue males bahas soal ini, so you guys
better read yourself. :))
Tulisan yang berjiwa nasionalis-anti feodal-feminis Pram baru benar-benar
menguat di tiga perempat bagian akhir buku. Gue sih (((curiga))) karakter Nyai
dan Minke dibuat sekuat itu untuk menonjolkan kesan pribumi yang berjuang untuk
dirinya sendiri di antara belantara feodalisme kolonial.
Pram menurut gue selalu berhasil
membangun karakter perempuan kuat dan menggambarkan betapa pedihnya feodalisme (dan
patriakhi) khususnya bagi perempuan. Makanya, karakter si Nyai ini lebih
populer ketimbang Minke. Emang “edan” kok si Nyai ini. Dia bukan hanya
bisa bertahan dengan status dan terpaan hidup, tapi juga menundukkannya. Dulu jadi
Nyai (gundik) itu ada tersirat rasa bangga. Namun, itu kebanggaan semu. Sebab setelah
dia tak lagi jadi Nyai, dia tak lagi punya akses pada strata sosial yang lebih
tinggi seperti sebelumnya. Malah, anak yang ia pelihara pun tak bisa diakui dan
dibawa serta.
Buat gue, adalah melegakan ketika
Bumi Manusia akhirnya berhasil diselesaikan selama hampir dari dua bulan, wkwk.
Sebuah pencapaian sebab menikmati tiap lembarnya harus disambi nyuapin dua
balita, atau nunggu bayi tidur di malah hari, atau malah dibawa ke kantor sama
suami buat dibaca ulang sama dia, atau sambil nenenin sampe mata gue juling, atau
tetiba dihujani boneka biar gue ga konsen baca hahah.
Oh iya, gue juga punya kutipan favorit
yang tentu saja bukan “adil sejak dalam pikiran” yang dikutip sejuta umat itu.
X))) Kutipan yang belakangan gue nemu juga di akunnya Iqbaal Ramadhan. Hahah.
(Jangan-jangan kita jodoh, Dek.)
Ini dia:
“Kalian boleh maju dalam pelajaran, mungkin mencapai
gelar kesarjanaan apa saja, tapi tanpa mencintai sastra, kalian tinggal hanya
hewan yang pandai.”
Juffrow Magda Peters, guru Bahasa dan Sastra Belanda.
(Bumi Manusia, hlm 313)[]